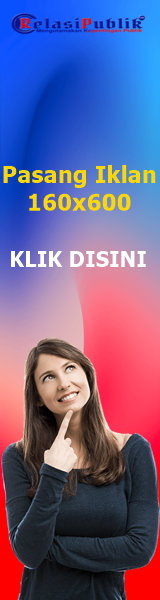Oleh: Desrimaiyanto
Lembah Harau bukan sekadar destinasi wisata; ia adalah puisi panjang yang ditulis alam, satu bait demi satu bait, sejak ratusan ribu tahun lalu. Terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, lembah ini seolah menjadi perantara antara langit dan bumi. Dinding-dinding granit yang menjulang hingga 150 meter, berselimut hijau tropis dan dihiasi air terjun yang tak jemu mengalir, menjadi pengingat bahwa ada bentuk keindahan yang tidak bisa digantikan layar ponsel atau bingkai digital.
Ketika banyak objek wisata membangun daya tarik dari sentuhan manusia—resor mewah, instalasi seni, spot swafoto yang seragam—Harau berdiri sebagai antitesis. Ia tidak dibuat, melainkan diwariskan. Dan justru karena itu, daya pikatnya lebih jujur dan mendalam. Harau tidak berusaha memikat; ia membiarkan alamnya bekerja, dan orang datang karena tergerak, bukan sekadar tergoda.
Yang menarik, Lembah Harau bukan hanya tempat pelarian dari kebisingan kota. Ia adalah ruang dialog. Di sini, orang bisa bertanya ulang tentang makna “kemajuan”, ketika melihat sawah menghampar damai di bawah tebing raksasa. Di sini pula, kesadaran ekologi tumbuh bukan dari buku, melainkan dari desir angin yang membawa aroma hutan dan tanah basah.
Namun Harau juga sedang diuji. Popularitasnya naik, dan bersamanya, datang ancaman klasik: komersialisasi tanpa kendali, pembangunan yang menafikan keseimbangan ekosistem, serta hilangnya narasi kearifan lokal. Maka, siapa pun yang mencintai Harau, bukan hanya datang untuk menikmati, tapi juga menjaga. Karena seperti semua keindahan yang murni, Harau hanya akan bertahan jika manusia belajar menahan diri.
Lembah Harau adalah pelajaran—bahwa yang paling indah dalam hidup ini sering kali hadir dalam kesunyian, dalam kesederhanaan yang penuh hormat pada alam.