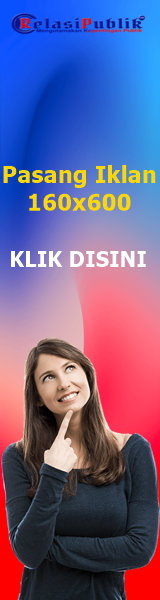Oleh: Novita sari yahya
Pernyataan seorang queen internasional bahwa “kami tidak berbicara, tetapi berjalan” disampaikan dengan keyakinan yang nyaris khidmat. Kalimat itu mengalir lembut, tidak menyinggung siapa pun, dan dengan mudah diterima sebagai bentuk kebijaksanaan modern. Namun justru karena kelembutannya itulah pernyataan tersebut layak direnungkan lebih jauh. Sebab di balik keanggunan kata-kata, tersembunyi sebuah pengakuan yang, bila dicermati dengan jujur, menyiratkan kekalahan pikiran di hadapan tubuh.
Saya termenung cukup lama mendengar pernyataan itu. Bukan karena terpesona, melainkan karena ia terasa terlalu selesai. Seolah-olah manusia telah diringkas menjadi postur, langkah, dan sorot mata. Padahal, dalam hampir seluruh kajian psikologi kognitif dan filsafat komunikasi, berbicara adalah tindakan yang paling manusiawi. Ketika seseorang berbicara, ia sedang membuka isi kepalanya kepada dunia, dengan segala risiko disalahpahami, disanggah, atau bahkan ditertawakan. Berbicara menuntut keberanian, karena di sanalah pikiran dipertaruhkan.
Berjalan, sebaliknya, adalah tindakan yang aman. Ia tidak dapat diperdebatkan. Ia tidak bisa diuji kebenarannya. Ia hanya bisa dinilai secara estetis. Dalam dunia yang semakin lelah berpikir, estetika menjadi jalan pintas yang menenangkan. Tidak perlu argumen, cukup impresi. Tidak perlu makna, cukup citra.
Dalam psikologi komunikasi, berjalan di panggung entah disebut catwalk, carriage, atau presence memang diakui sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Ia menyampaikan pesan tentang kepercayaan diri, disiplin, dan kendali diri. Namun persoalan muncul ketika komunikasi nonverbal diangkat menjadi pengganti total komunikasi verbal. Ketika tubuh diberi mandat penuh untuk mewakili keseluruhan manusia, pikiran pun perlahan dipinggirkan sebagai beban yang tidak efisien.
Ironisnya, pada saat yang hampir bersamaan, dunia pageantry juga menggemakan pentingnya public speaking. Seorang pengajar dengan yakin menyatakan bahwa public speaking adalah ilmu komunikasi dengan manusia. Pernyataan ini sepintas terdengar mulia. Namun seperti banyak slogan indah lainnya, ia menjadi bermasalah ketika maknanya dipersempit. Yang diajarkan kemudian bukanlah komunikasi yang mendidik, melainkan teknik menata kata agar terdengar tepat, aman, dan mengesankan.
Di sinilah letak perbedaannya. Komunikasi edukatif berangkat dari pemikiran yang hidup. Ia lahir dari proses membaca, mengamati, dan berani mengambil sikap. Sementara komunikasi yang sekadar menata kata berangkat dari strategi citra. Kata-kata dipilih bukan karena kebenarannya, melainkan karena keamanannya. Kalimat dirangkai bukan untuk menyampaikan gagasan, tetapi untuk menghindari kesalahan.
Perbedaan ini tampak sepele, tetapi dampaknya serius. Ketika public speaking direduksi menjadi seni menyenangkan audiens, ia berubah menjadi permainan psikologis. Pikiran tidak lagi dikembangkan, melainkan dikendalikan. Kontestan tidak didorong untuk berpikir kritis, tetapi untuk terdengar kritis. Kebenaran tidak dicari, melainkan disesuaikan.
Dalam psikologi sosial, kondisi ini dikenal sebagai impression management. Individu mengatur perilaku dan bahasa untuk membentuk kesan tertentu. Dalam batas tertentu, hal ini adalah keterampilan sosial yang wajar. Namun ketika impression management menggantikan kejujuran intelektual, ia menjadi manipulasi halus. Seseorang tampak cerdas tanpa harus berpikir mendalam, tampak peduli tanpa perlu memahami persoalan.
Di titik inilah pernyataan “kami tidak berbicara, tetapi berjalan” menemukan makna satirnya yang paling tajam. Ia bukan sekadar metafora tentang kehadiran, melainkan pengakuan tentang penghindaran. Berjalan memungkinkan seseorang hadir tanpa berpendapat. Ia memberi ruang bagi pujian tanpa membuka peluang kritik.
Dunia pageantry sering mengklaim dirinya sebagai ruang pemberdayaan perempuan. Namun pemberdayaan seperti apa yang lebih menghargai keindahan langkah daripada keberanian berpikir? Jika pemberdayaan berarti otonomi intelektual, maka sistem yang membatasi pikiran demi citra sejatinya adalah sistem penjinakan yang dibungkus keanggunan.
Aristoteles, berabad-abad sebelum istilah personal branding ditemukan, telah merumuskan tiga pilar retorika: logos, ethos, dan pathos. Logos adalah nalar, ethos adalah karakter, dan pathos adalah emosi. Dalam praktik pageantry modern, pathos dirawat dengan serius. Air mata dilatih, empati dikurasi, dan emosi ditampilkan dengan presisi. Ethos dipoles melalui narasi diri yang rapi. Namun logos kerap menjadi elemen paling rapuh.
Tidak mengherankan jika jawaban-jawaban yang muncul terdengar sempurna tetapi terasa kosong. Semua berbicara tentang perdamaian, pendidikan, dan kemanusiaan, tanpa satu pun posisi yang berani. Dunia digambarkan seolah-olah tanpa konflik, tanpa ketidakadilan, dan tanpa korban. Bukan karena para queen tidak peduli, melainkan karena mereka diajarkan bahwa berpikir terlalu jauh adalah risiko reputasi.
Dalam situasi ini, public speaking kehilangan fungsi etiknya. Ia tidak lagi menjadi sarana dialog, melainkan alat bertahan. Kata-kata digunakan untuk melindungi citra, bukan untuk menguji gagasan. Keindahan bahasa menutupi ketiadaan keberpihakan.
Satire ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan individu. Ia ditujukan pada sistem yang lebih mencintai kepatuhan yang indah daripada kecerdasan yang jujur. Sistem yang lebih nyaman dengan kalimat aman daripada kebenaran yang mengganggu. Dalam sistem seperti ini, queen tidak disiapkan sebagai pemikir publik, melainkan sebagai simbol estetika.
Padahal, jika peran queen ingin dimaknai lebih dari sekadar dekorasi global, ia sejatinya adalah diplomat budaya. Seorang diplomat tidak hanya hadir dengan postur yang tepat, tetapi dengan argumen yang jernih. Jalannya adalah simbol martabat, tetapi bicaranya adalah ukuran integritas. Tanpa pikiran, martabat hanyalah ornamen.
Jika seseorang hanya berjalan, ia menggunakan tubuhnya untuk menarik perhatian. Namun ketika seseorang berbicara dengan pikiran yang jujur, ia mengundang orang lain untuk berpikir. Di antara keduanya, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani berbicara, meski dengan risiko.
Keanggunan sejati tidak lahir dari kesenyapan intelektual, melainkan dari keberanian menyatukan tubuh dan pikiran dalam satu garis integritas. Di sanalah mahkota menemukan maknanya, bukan sebagai hiasan kepala, melainkan sebagai simbol tanggung jawab berpikir.
Daftar Pustaka
1. Aristoteles. (2007). On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. New York: Oxford University Press
2. Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor Books.
3. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). Theories of Human Communication. Long Grove: Waveland Press.
4. Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person. Boston: Houghton Mifflin.
5. DeVito, J. A. (2019). The Interpersonal Communication Book. Boston: Pearson Education.
6. Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.