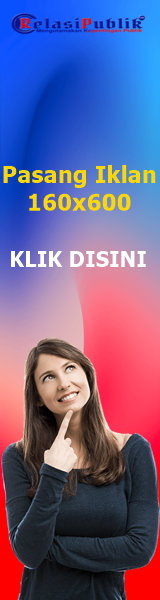Oleh: Novita sari yahya
Sumatera Barat kembali terguncang. Pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengenai banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah bukan sekadar laporan bencana, melainkan tudingan serius atas rekam jejak kebijakan publik yang dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis.
WALHI menyingkap bagaimana pemberian izin, pengelolaan ruang, serta kebijakan pembangunan yang longgar terhadap kepentingan lingkungan berkontribusi pada kerentanan bencana yang kini ditanggung masyarakat.
Dalam konteks ini, bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa alam semata. Ia adalah akumulasi dari keputusan administratif, tanda tangan pejabat, dan kebijakan yang pada suatu waktu mungkin terlihat legal, namun pada akhirnya berdampak fatal bagi kehidupan manusia. Pertanyaan etis yang muncul bukan hanya “siapa yang salah”, melainkan “siapa yang bertanggung jawab”.
Kebijakan Publik dan Pilihan saya.
Ketika saya memilih fokus pada isu kebijakan publik, tidak sedikit kritik yang datang, terutama karena latar belakang profesi saya berasal dari dunia kedokteran. Sebagian orang beranggapan bahwa urusan kebijakan, anggaran, dan tata kelola pemerintahan seharusnya menjadi domain birokrat atau politisi, bukan tenaga medis. Namun bagi saya, bekerja bukanlah sekadar pencarian materi atau pengakuan sosial, melainkan soal kemanfaatan.
Dalam dunia kesehatan, kami terbiasa melihat hubungan langsung antara kebijakan dan nyawa manusia. Sebuah keputusan administrasi yang buruk dapat berarti obat tidak tersedia, layanan tidak terjangkau, atau pasien kehilangan kesempatan hidup. Prinsip yang sama berlaku dalam kebijakan lingkungan dan tata ruang. Ketika izin diberikan tanpa pertimbangan ekologis yang matang, maka risiko yang muncul bukan sekadar kerusakan alam, tetapi penderitaan manusia.
Jika ditanya apa yang memberi kepuasan dalam kerja kebijakan publik, jawaban saya sederhana. Saya merasa puas ketika tetangga atau orang yang saya kenal terbantu oleh keberadaan BPJS Kesehatan. Ketika mereka tidak lagi takut pergi ke rumah sakit karena persoalan biaya, di situlah saya merasakan makna dari kerja kebijakan. Kepuasan itu tidak bisa diukur dengan materi. Bahkan jika secara finansial dunia penelitian dan advokasi kebijakan jauh dari kemewahan, saya tetap merasa cukup.
Jabatan, Anggaran, dan Beban Tanda Tangan
Tidak dapat dimungkiri bahwa birokrasi menawarkan daya tarik tersendiri. Jabatan struktural menjanjikan kekuasaan, akses anggaran, dan kewenangan untuk memberikan izin. Mengajukan anggaran, menandatangani dokumen, serta mengeluarkan rekomendasi adalah rutinitas yang terlihat administratif. Namun di balik setiap tanda tangan, sesungguhnya melekat tanggung jawab yang sangat besar.
Setiap izin yang diberikan, setiap rekomendasi yang diteken, akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan hukum dan publik, tetapi juga di hadapan nilai moral dan, bagi mereka yang beriman, di hadapan Tuhan. Tanda tangan bukan sekadar goresan tinta. Ia adalah keputusan yang bisa menyelamatkan atau justru mengorbankan kehidupan banyak orang.
Dalam kasus banjir bandang di Sumatera Barat, video seorang ibu dengan wajah murung dan mata sembab menjadi potret paling jujur dari kegagalan kebijakan. Saat diwawancarai, ia menangis karena kehilangan rumah—satu-satunya tempat berlindung dari hujan dan panas yang hilang ditelan banjir. Kehilangan itu tidak bisa ditebus dengan sekadar bantuan sembako, makanan siap saji, atau program trauma healing jangka pendek.
Luka yang Tak Terlihat
Penderitaan korban bencana sering kali disederhanakan menjadi angka statistik: jumlah rumah rusak, korban mengungsi, atau nilai kerugian materi. Padahal ada luka yang tidak kasatmata, luka yang hidup dalam doa-doa mereka setiap hari. Luka itu hadir dalam rasa tidak aman, dalam ketakutan setiap kali hujan turun, dan dalam pertanyaan tentang keadilan.
Dalam tradisi keagamaan, doa orang yang teraniaya memiliki tempat yang sangat istimewa. Ia diyakini menembus batas, langsung sampai kepada Yang Mahakuasa. Karena itu, ajaran agama juga mengingatkan bahwa kezaliman termasuk kezaliman yang lahir dari kebijakan adalah penghalang keselamatan spiritual. Tidak sedikit orang saleh secara ritual, namun terjerumus oleh keputusan administratif yang mengorbankan sesama.
Di sinilah pentingnya pertimbangan moral dalam kepemimpinan. Manusia tidak seharusnya didorong menduduki jabatan hanya karena kepatuhan dan loyalitas. Jabatan publik semestinya diisi oleh mereka yang pantas memimpin, yang memahami bahwa satu tanda tangan dapat menyelamatkan atau menghancurkan kehidupan jutaan orang.
Belajar dari Mohammad Natsir
Sejarah Indonesia menyediakan banyak teladan kepemimpinan yang berakar pada kesederhanaan dan integritas. Salah satu figur yang relevan untuk direnungkan adalah Mohammad Natsir. Ia dikenal sebagai sosok menteri dengan kemeja bertambal, simbol hidup sederhana di tengah kekuasaan. Ada kisah yang jarang diceritakan secara luas: bagaimana tanda tangan dan diplomasi Natsir berkontribusi pada pemulihan ekonomi Jepang pasca-Perang Dunia II. Berita wafatnya Natsir bahkan membuat sebagian rakyat Jepang tertunduk sedih, sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Ia melakukan kebaikan tanpa sorak-sorai, tanpa pencitraan, dan tanpa pesta kemewahan.
Mengapa Natsir mampu melakukan kebaikan dan tidak ada kritikan?. Salah satu jawabannya terletak pada konsistensi hidupnya. Ia mencontohkan kesederhanaan, menjaga jarak dari kemewahan, dan menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Integritas personal itu memberi legitimasi moral pada setiap keputusan yang ia ambil.
Kontras Kepemimpinan Hari Ini
Bandingkan dengan realitas hari ini. Ketika pemimpin memamerkan pesta meriah dan gaya hidup mewah, terutama yang ditampilkan oleh keluarga dekat, publik dengan mudah memahami mengapa keputusan-keputusan penting sering kali diambil tanpa pertanyaan kritis. Dalam situasi seperti itu, tanda tangan menjadi rutinitas administratif, bukan lagi perenungan etis.
Ketika bencana terjadi, respons yang muncul sering kali berupa pembelaan diri. Argumen bahwa “tidak semua kebijakan diketahui” atau “itu di luar kewenangan saya” menjadi tameng yang berulang. Padahal masyarakat tidak selalu menuntut kesempurnaan. Yang mereka harapkan adalah kejujuran dan empati. Sesungguhnya, satu kalimat pun sudah cukup untuk menunjukkan tanggung jawab moral: “Saya meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat atas tragedi banjir bandang ini, terlepas apakah seluruh kebijakan tersebut berada dalam pengetahuan atau kewenangan saya. Saya akan berusaha memperbaikinya.”
Kalimat sederhana itu memiliki daya penyembuh yang jauh lebih besar daripada seribu pembelaan teknokratis.
Penutup: Etika di Atas Legalitas
Bencana alam akan selalu ada. Namun bencana kemanusiaan akibat kebijakan yang abai adalah sesuatu yang bisa dicegah. WALHI, dengan segala kritiknya, sesungguhnya sedang mengingatkan bahwa pembangunan tanpa etika adalah jalan pintas menuju penderitaan kolektif. Kepemimpinan bukan soal seberapa banyak izin yang ditandatangani atau proyek yang diresmikan, melainkan seberapa besar keberanian untuk menolak kebijakan yang berpotensi merusak kehidupan.
Dalam konteks Sumatera Barat, refleksi ini menjadi sangat mendesak. Sebab setiap hujan yang turun kini membawa bukan hanya air, tetapi juga ingatan akan keputusan-keputusan masa lalu. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab. Dan di hadapan penderitaan manusia, tidak ada tanda tangan yang benar-benar netral.
Daftar Pustaka
WALHI. (2024). Banjir dan longsor: WALHI bongkar rekam jejak kebijakan Mahyeldi. SumbarPost.
Partai Masyumi. (2023). Kisah Pak Natsir yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah.
Tribun Sumbar. (2020). Surat Natsir dari penjara: Jadikan Jepang raksasa otomotif.
https://www.tribunsumbar.com/berita/33359/surat-natsir-dari-penjara-jadikan-jepang-raksasa-otomotif/halaman/6
Indonesia Inside. (2024). Kisah Buya Natsir: Usahakan 1.000 sarung untuk orang tahanan PKI yang tobat.
https://indonesiainside.id/khazanah/2024/05/10/kisah-buya-natsir-usahakan-1-000-sarung-untuk-orang-tahanan-pki-yang-tobat