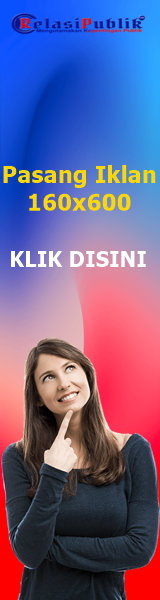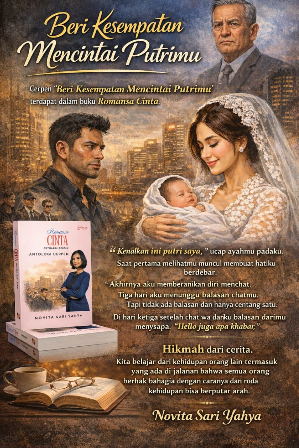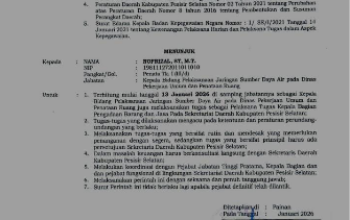Oleh: Novita Sari Yahya
Subtema: Feodalisme, Kolonialisme, dan Ingatan Kolektif yang Terus Hidup
Pertentangan kelas sosial merupakan tema yang berulang dan nyaris tak pernah usang dalam sejarah Indonesia. Tema ini tidak hanya hadir dalam kajian akademik atau wacana politik, tetapi juga hidup dalam karya sastra, termasuk cerpen. Alasan kemunculannya sering kali sederhana, berangkat dari pengalaman sehari-hari dan pengamatan langsung terhadap struktur masyarakat yang timpang. Budaya feodalisme yang masih kental hingga hari ini menjadi salah satu sumber utama konflik kelas yang terus berulang, baik secara halus maupun terbuka.
Feodalisme di Indonesia bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang masih mengakar dalam relasi sosial. Ia tercermin dalam cara masyarakat memandang kekuasaan, status, dan kehormatan. Hubungan antara atasan dan bawahan, orang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat kecil sering kali tidak setara. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolik. Bahasa, sikap tubuh, hingga akses terhadap pendidikan dan keadilan menjadi penanda kelas sosial yang sulit ditembus.
Pertarungan kelas di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonialisme, struktur masyarakat dibangun secara hierarkis untuk kepentingan penjajah. Golongan Eropa ditempatkan di puncak, disusul kelompok Timur Asing, dan pribumi di lapisan terbawah. Sistem ini melahirkan ketidakadilan struktural yang sistematis. Rakyat pribumi diposisikan sebagai tenaga kerja murah, sementara sumber daya alam dieksploitasi tanpa memberi kesejahteraan yang layak bagi mereka.
Sastra menjadi salah satu medium penting untuk merekam dan mengkritik situasi tersebut. Pramoedya Ananta Toer melalui Bumi Manusia menggambarkan dengan tajam bagaimana pertarungan kelas bekerja dalam kehidupan tokoh-tokohnya. Minke, sebagai tokoh utama, berada di persimpangan kelas. Ia seorang pribumi terdidik yang berusaha menembus batas feodalisme dan kolonialisme. Melalui kisahnya, Pramoedya menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran tidak selalu cukup untuk membebaskan seseorang dari belenggu struktur sosial yang timpang.
Setelah kemerdekaan, pertarungan kelas tidak serta-merta berakhir. Bentuknya berubah, tetapi esensinya tetap sama. Konflik antara pemilik modal dan buruh, antara elite politik dan rakyat kecil, terus terjadi. Gerakan kelas sempat menemukan momentumnya pada masa awal kemerdekaan, terutama melalui organisasi buruh, tani, dan perempuan. Organisasi-organisasi ini berupaya memperjuangkan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Namun, peristiwa 1965 menjadi titik balik yang menentukan. Gerakan kelas diberangus secara brutal. Tidak hanya individu yang menjadi korban, tetapi juga gagasan tentang perlawanan kelas itu sendiri. Orde Baru kemudian membangun narasi stabilitas sebagai syarat utama pembangunan ekonomi. Dalam kerangka ini, organisasi buruh dijadikan tunggal, organisasi perempuan diseragamkan, dan berbagai bentuk gerakan sosial dikontrol ketat oleh negara. Stabilitas politik ditempatkan di atas kebebasan berserikat dan berekspresi.
Pembangunan ekonomi yang dijalankan Orde Baru memang menghasilkan pertumbuhan, tetapi tidak selalu diiringi pemerataan. Kesenjangan sosial justru semakin melebar. Sebagian kecil masyarakat menikmati hasil pembangunan, sementara sebagian besar lainnya tetap berada di posisi rentan. Feodalisme menemukan bentuk barunya dalam relasi antara penguasa dan pengusaha, antara negara dan rakyat. Kekuasaan dan modal saling menguatkan, menciptakan kelas elite yang sulit disentuh oleh hukum.
Dalam konteks inilah cerpen dengan tema pertentangan kelas sosial menemukan relevansinya. Cerpen tidak harus berbicara tentang peristiwa besar atau tokoh penting. Kisah tentang cinta yang terhalang status sosial, konflik keluarga karena perbedaan kelas, atau pergulatan batin seseorang yang terjebak antara idealisme dan realitas ekonomi sudah cukup untuk memotret ketimpangan yang ada. Justru melalui cerita-cerita kecil, pembaca diajak melihat dampak nyata dari struktur sosial yang timpang.
Menulis cerpen tentang pertentangan kelas juga menjadi upaya menjaga ingatan kolektif. Sejarah sering kali ditulis dari sudut pandang pemenang, sementara suara mereka yang kalah dan terpinggirkan diabaikan. Sastra memberi ruang bagi suara-suara tersebut untuk tetap hidup. Ia tidak selalu menawarkan solusi, tetapi menghadirkan pertanyaan dan kegelisahan yang perlu direnungkan bersama.
Budaya feodalisme yang masih bertahan menunjukkan bahwa pertarungan kelas bukan sekadar persoalan masa lalu. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita memandang sesama, dalam kebijakan publik, dan dalam relasi kerja. Dengan menuliskannya dalam cerpen, penulis tidak hanya bercerita, tetapi juga melakukan kritik sosial. Cerpen menjadi cermin yang memantulkan wajah masyarakat apa adanya, lengkap dengan luka dan kontradiksinya.
Pada akhirnya, pertentangan kelas sosial adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah Indonesia. Ia terus berubah bentuk, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Sastra, termasuk cerpen, memiliki peran penting untuk merekam, mempertanyakan, dan mengingatkan. Selama ketimpangan masih ada, selama feodalisme masih hidup dalam struktur masyarakat, tema pertarungan kelas akan selalu menemukan ruangnya dalam karya sastra Indonesia.
Profil Novita Sari Yahya
Penulis dan Peneliti
Buku yang Diterbitkan:
1. Romansa Cinta Antologi 23 Cerpen
2. Padusi: Alam Takambang Jadi Guru
3. Novita & Kebangsaan
4. Ibu Bangsa, Wajah Bangsa
5. Perempuan Indonesia, Zamrud Khatulistiwa
6. Self Love: Rumah Perlindungan Diri
7. Makna di Setiap Rasa: Antologi Puisi
8. Siluet Cinta, Pelangi Rindu
Pemesanan Buku: 089520018812
Lagu Rebel Hearts
Pencipta lagu : Gede Jerson
Berdasarkan puisi hitam putih cinta karya Novita sari yahya