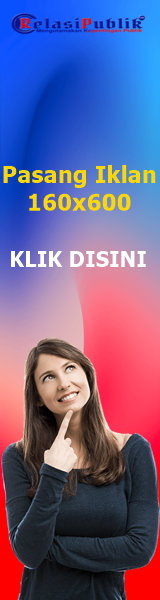Oleh: Dr. Agatha Jumiati, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh tayangan di salah satu stasiun televisi nasional yang dianggap menyinggung pesantren dan sosok kiai. Adegan dan narasi yang diputar mengandung unsur stereotip negatif, menggambarkan pesantren sebagai tempat kolot, tidak higienis, atau bahkan sarang kekerasan.
Reaksi publik pun keras. Para santri, alumni, dan ormas Islam menyuarakan keberatan. Sebagian menuntut klarifikasi dan sanksi hukum atas tayangan tersebut. Namun di sisi lain, pihak televisi berdalih bahwa hal itu adalah bentuk “kebebasan berekspresi dan karya seni.”
Lalu, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum media?
Indonesia menjamin kebebasan berekspresi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Namun, UUD juga menegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) bahwa setiap hak harus dibatasi oleh penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain serta nilai-nilai moral dan agama. Kebebasan pers dan siaran tidak bisa dimaknai sebagai hak absolut.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas mengatur bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati norma agama, budaya, dan martabat bangsa. Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran menegaskan: “Isi siaran dilarang merendahkan martabat manusia, melecehkan nilai-nilai agama, atau mengandung fitnah.”
Dengan demikian, setiap siaran yang menggambarkan pesantren atau kiai secara negatif tanpa dasar faktual yang kuat bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administratif bahkan etik penyiaran.
Lembaga penyiaran di Indonesia berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pedoman ini jelas menyebut bahwa media tidak boleh menyiarkan konten yang:
1. Menista agama atau simbol keagamaan.
2. Merendahkan kelompok sosial atau lembaga pendidikan keagamaan.
3. Menyudutkan tokoh agama tanpa klarifikasi dan fakta yang berimbang.
Artinya, stasiun televisi yang menayangkan konten satir atau pelecehan terhadap pesantren atau kiai melanggar prinsip etika penyiaran. Dalam hukum administrasi, pelanggaran ini bisa berujung pada teguran, penghentian program, denda administratif, atau pencabutan izin siar. Namun, pelanggaran semacam ini bukan hanya soal etika lembaga penyiaran, tetapi juga soal penghormatan terhadap kehormatan publik dan tokoh keagamaan.
Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan institusi sosial yang diakui oleh negara.
Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menyatakan bahwa pesantren memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Begitu pula, kiai sebagai pengasuh pesantren adalah tokoh publik yang memiliki kehormatan sosial dan moral.
Ketika media menayangkan konten yang menistakan peran atau karakter kiai, maka secara hukum dapat dianggap melanggar hak konstitusional atas kehormatan dan martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945.
Dalam ranah hukum pidana, tindakan itu bahkan bisa masuk kategori:
Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), jika dilakukan secara terbuka di media.
Penyebaran kebencian terhadap golongan tertentu (Pasal 156 KUHP), bila menyerang komunitas agama atau pesantren secara sistematis.
Dengan kata lain, media tidak kebal hukum. Kebebasan berekspresi tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan hukum publik.
Industri penyiaran sering bersembunyi di balik dalih “kreativitas”, padahal yang dikejar hanyalah rating dan sensasi. Padahal, hukum penyiaran menempatkan media sebagai penyampai nilai edukatif, bukan provokatif. Siaran yang menyinggung pesantren dan kiai mencerminkan dua persoalan serius:
1. Krisis literasi budaya di ruang redaksi. Banyak produser dan penulis naskah tidak memahami sensitivitas agama dan tradisi pesantren.
2. Rendahnya kesadaran etika hukum media. Program disusun tanpa telaah hukum, seolah UU Penyiaran hanya formalitas.
KPI dan Dewan Pers tidak cukup hanya memberi peringatan. Harus ada langkah hukum konkret agar media benar-benar jera. Siaran publik adalah wilayah hukum public, bukan ruang eksperimen komedi atau provokasi.
Agar peristiwa seperti ini tak berulang, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan:
1. Pendidikan hukum media bagi insan penyiaran. Setiap lembaga penyiaran wajib memastikan produser, penulis, dan editor memahami regulasi penyiaran dan etika agama.
2. Dialog antara KPI, ormas Islam, dan lembaga pesantren. Bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk membangun cultural awareness dan mencegah konflik sosial.
3. Penguatan regulasi sanksi penyiaran. UU Penyiaran dan P3SPS perlu direvisi agar pelanggaran yang menyinggung kelompok keagamaan tidak berhenti di teguran administratif, tapi bisa berlanjut ke sanksi pidana atau perdata.
Media adalah cermin bangsa. Bila cerminnya retak karena satire yang melukai, maka yang terlihat bukan wajah demokrasi, melainkan wajah arogan kebebasan. Kebebasan berekspresi adalah hak, tapi menghormati keyakinan dan kehormatan orang lain adalah kewajiban. Pesantren dan kiai bukan sekadar simbol agama, melainkan penjaga moral publik. Menistakan mereka lewat siaran televisi bukan hanya melanggar etika, tetapi juga melukai nilai-nilai hukum dan kemanusiaan yang dijunjung konstitusi.