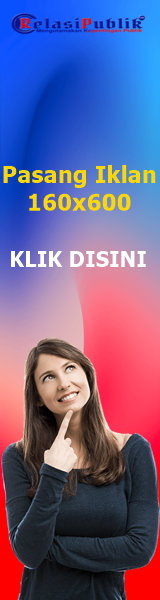Wildan, S.E., M.I.Kom
Praktisi Humas Pemerintah dan Pemerhati Media
Minimnya kemampuan literasi masyarakat Indonesia hampir disemua kalangan, merupakan masalah utama di Indonesia saat ini.
Menurut hasil survey UNESCO, minat baca di Indonesia pada tataran 0, 001 % persen, artinya hanya 1 dari 1000 orang Indonesia memiliki minat baca.
Hasil survey tersebut diperkuat riset PISA, yang mengatakan nilai literasi Indonesia hanya 396 di dunia, berada pada peringkat 2 paling bawah. Sementara itu, Indonesia salah satu pengguna media sosial tertinggi di dunia.
Di negri ini pengguna Facebook lebih dari 130 juta, IG lebih dari 53 juta (We Are Social) , Twitter 41,96 juta (Kata Data), urutan ketiga di dunia, jadi tak heran Indonesia termasuk negara yang “paling berisik” di dunia maya.
Keberisikan itulah adalah salah satu bukti kurangnya literasi, warganet sangat gampang terusik dengan sebuah artikel, komentar, bahkan hoax, yqng mengakibatka sangat gampang marah.
Pada sisi pemberitaan terutama media on line banyak sekali ditemui “clickbait”, yaitu sebuah cara pemberitaan dimana antara judul berita dengan isi berita tidak sama. Pembaca hanya disuguhi judul-judul yang sensasional dari sebuah berita namun esensi berita tersebut jauh panggang dari api.
Bagi masyarakat yang minim literasi, gak heran dengan “lugunya” dibagikan melalui akun media sosialnya dan mendapatkan beragam komentar.
Penulis mengamati, rata-rata akun yang menyebarkan berita mendapat respon yang sama dari followers-nya (pengikut), apa yang dikomentar dari berita yang dibagikan hampir senada dengan komentar yang diterimanya.
Media sosial Indonesia semakin berisik ketika musim Pemilihan Umum seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres. Semua pihak berlomba-berlomba merebut perhatian masyarakat melalui media sosial. Semua membuat opini melalui tulisan dan komentar. Namun hanya sedikit yang menampilkan referensi dan data dalam sebuah diskursus di media sosial.
Sering ditemukan akhir sebuah diskursus stersebut hanyalah debat kusir, bully, provokasi yang dapat menimbulkan hate spin (pelintiran kebencian) dam berujung hate speech.
Cherian George (2017), mendefinisikan hate spin penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan,dan digunakan sebagai strategi politik yang mengeksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan.
Dipeliharanya kebencian yang meluas dalam kelompok memiliki tujuan yang bermacam-macam.
Media sosial menjadi salah satu tempat untuk memanfaatkan hate spin ini, sebagai bentuk nyata adalah melalui hate speech (ujaran kebencian) dari akun media sosial secara kolektif. Yang paling jelas, ujaran kebencian mengintimidasi kelompok-kelompok luar (out-groups) dan menjadi landasan bagi persekusi mereka. Inilah yang menjadi keberisikan.
Ancaman UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 perlu menjadi perhatian bagi kita semua, agar kita jangan sampai terjebak didalam diskursus hate spin dan memancing kita melakukan hate speech di media sosial.
Sudah banyak yang menjadi sasaran penegakkan hukum dari aturan ini, baik yang benar-benar bersalah maupun yang tidak sengaja melakuan kesalahan.
Apa yang harus dilakukan dengan hal ini? Perbanyak literasi lagi. Jangan hanya terpaku pada salah satu sumber informasi. Kita harus membiasakan melakukan perbandingan terhadap data dan informasi yang ada. Dengan meliterasi, kita tidak akan menari digendang orang lain. Bisa menciptakan dialektika yang sehat, elegan dan mencerdaskan sekaligus ladang amal.
Janganlah membuat tulisan dan komentar yang “katakanlah” sensasional atau provokasi tapi tidak mampu mempertanggungjawabkannya.
Media sosial telah mengubah kultur masyarakat, semuanya bisa menjadi jurnalis,CITIZEN JOURNALIST. Dan media sosial juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi bangsa ini. Ibarat sebuah pisau, media sosial dapat digunakan untuk kebaikan namun juga dapat digunakan untuk kejahatan. Literasi adalah kunci.****