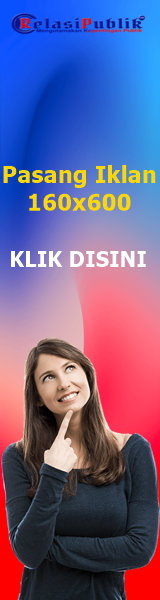Oleh: FX. Hastowo Broto Laksito, S.H, M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
Beberapa waktu lalu, jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video: seorang pria muda tertangkap basah mencuri di sebuah minimarket. Namun, alih-alih menuai hujatan seperti kasus serupa, kolom komentar justru dipenuhi kalimat simpatik Sayang banget, padahal ganteng.” Ada yang menulis, “Kalau dia minta maaf, maafin aja deh, kasihan.”
Bahkan ada yang bercanda, “Nggak apa-apa nyuri, asal wajahnya begini”. Fenomena ini membuat banyak orang terdiam. Apakah wajah bisa menjadi alasan untuk menghapus kesalahan? Apakah ketampanan mampu menundukkan rasa keadilan kita? Ataukah ini cerminan bagaimana publik perlahan memaknai hukum bukan sebagai nilai, melainkan sebagai selera?
Dalam hukum pidana, mencuri adalah tindak kejahatan yang diatur tegas dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.” Tidak ada pasal tambahan berbunyi, “…kecuali jika pelaku ganteng atau menarik.” Artinya, hukum tidak mengenal wajah, status sosial, atau rasa iba. Yang diadili adalah perbuatannya, bukan penampilannya. Namun, media sosial bekerja dengan logika berbeda. Di ruang digital, citra sering kali lebih berkuasa daripada substansi. Publik cepat tergerak oleh simpati visual wajah tampan, ekspresi menyesal, atau gestur sopan. Padahal, empati yang salah arah justru bisa mengikis rasa keadilan substantif yang menjadi dasar sistem hukum.
Fenomena ini bukan hal baru dalam psikologi sosial. Ini disebut “halo effect” dimana kecenderungan menilai seseorang secara positif hanya karena satu atribut menarik, seperti wajah atau penampilan. Efek ini membuat masyarakat cenderung memaafkan pelaku “menarik” dan menghukum lebih keras mereka yang dianggap “tidak menarik”. Dalam konteks hukum dan keadilan, ini berbahaya. Sebab keadilan sejatinya harus netral, objektif, dan tanpa pandang bulu. Jika rasa kasihan didasarkan pada penampilan, maka kita sedang membuka ruang bagi diskriminasi emosional: yang tampan dimaafkan, yang kumal dipenjara. Padahal, dalam hukum pidana Indonesia, yang menjadi pertimbangan adalah niat, akibat, dan kerugian, bukan rupa wajah atau simpati massa.
Bukan berarti hukum harus keras tanpa ampun. Sistem hukum modern juga mengenal konsep keadilan restoratif dimana pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku secara manusiawi. Jika pelaku benar-benar mencuri karena kebutuhan mendesak, misalnya lapar atau kesulitan ekonomi, maka penegak hukum dapat mempertimbangkan langkah mediasi dan pembinaan. Namun, keputusan itu harus lahir dari proses hukum yang sah, bukan dari tekanan netizen atau simpati buta. Rasa kasihan boleh ada, tetapi tidak boleh menggantikan proses hukum.
Sebab ketika empati menggantikan prinsip, maka keadilan berubah menjadi hiburan.
Media sosial sering kali memperlakukan kejahatan kecil sebagai bahan tontonan. Ketika netizen ramai-ramai “membela” pelaku karena faktor penampilan, tanpa disadari mereka sedang menormalisasi pencurian kecil. Padahal, setiap tindakan melawan hukum sekecil apa pun jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, dapat menular menjadi perilaku sosial yang lebih besar. Hari ini kita menoleransi pencuri karena “ganteng”, besok mungkin karena “lucu”, lusa mungkin karena “terkenal”. Jika standar moral bergeser dari hukum ke rasa suka, maka masyarakat kehilangan arah etiknya.
Kasus maling di minimarket ini seharusnya menjadi cermin, bukan tontonan. Fenomena ini memperlihatkan dua hal: Pertama, bahwa kemiskinan dan tekanan sosial masih nyata sebab tak seorang pun terlahir ingin mencuri. Kedua, bahwa empati publik sering kali salah sasaran, lebih sibuk pada rupa daripada akar masalah. Hukum memang harus manusiawi, tetapi juga harus tegas. Manusiawi berarti memahami konteks tegas yang berarti menjaga prinsip. Keduanya tak bisa dipisahkan. Sebab tanpa ketegasan, hukum hanya jadi nasihat. Tanpa kemanusiaan, hukum jadi alat kekuasaan. Dan tanpa akal sehat publik, hukum kehilangan pijakannya di hati masyarakat.
Dalam negara hukum, keadilan tidak mengenal wajah. Keadilan tidak tunduk pada penampilan, tidak terpesona oleh ketampanan, dan tidak melemah oleh rasa kasihan yang salah arah. Mungkin benar, si pelaku tampan. Mungkin ia menyesal. Tapi hukum tidak dibangun untuk menilai tampilan luar, melainkan untuk menjaga nilai-nilai dalam kejujuran, tanggung jawab, dan rasa aman bagi sesama warga. Keadilan sejati tidak memihak yang tampan atau buruk rupa. Keadilan hanya memihak pada kebenaran dan tanggung jawab.